Di sebuah dusun kecil yang sederhana, hiduplah seorang perempuan setengah baya yang dikenal dengan nama Inak Ma’nah. Wajahnya kurus, keriput mulai menyapa, namun sorot matanya menyimpan keteguhan yang sulit didefinisikan. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil berlantai tanah dan berdinding anyaman bambu. Tidak punya sumur, apalagi listrik yang memadai. Bahkan tanah tempat gubuknya berdiri pun bukan miliknya—hanya titipan dari tetangga yang berhati lapang.
Usianya sekitar lima puluhan, belum menikah, dan sebatang kara. Dulu, Inak Ma’nah sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota. Tapi usia tak bisa dilawan. Ketika tubuh tak lagi sekuat dulu, ia pulang kampung. Bersama ibunya yang renta, mereka membangun hidup dari nol. Tetangga bergotong royong membangunkan gubuk untuk mereka. Tak banyak, tapi cukup untuk berteduh.
Meski hidup dalam kemiskinan, Inak Ma’nah enggan berpangku tangan. Ia mulai menjual nasi bungkus untuk para santri di pesantren dekat rumah. Penghasilannya tak seberapa, tapi cukup untuk menyambung hidup. Dan yang mengejutkan: ia bahkan masih bisa menabung, meski hanya Rp5.000 atau Rp10.000 setiap bulan di Bank Perkreditan Rakyat tempat Haji Sanusi bekerja.
Setelah menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), tabungannya bertambah. Tak banyak memang, tapi saldo terakhirnya mencapai Rp650.000. Sore itu, Inak Ma’nah datang ke rumah Haji Sanusi. Ia duduk bersimpuh di lantai, seperti biasa.
“Pak, saya mau ambil tabungan,” katanya pelan.
"Sudah sore, bank tutup. Bagaimana kalau Senin?" jawab Haji Sanusi.
“Senin juga tidak apa-apa, saya tidak buru-buru.”
“Mau ambil berapa?”
“Enam ratus ribu, Pak,” jawabnya lirih.
Haji Sanusi terdiam sejenak. “Untuk apa?”
Inak Ma’nah tersenyum malu, menunduk. “Saya mau beli kambing kurban, Pak. Saya tambahkan dengan uang saya yang di rumah, insya Allah cukup.”
Haji Sanusi terdiam lebih lama. Bukan karena menolak, tapi karena terharu. Di hadapannya, seorang perempuan miskin ingin menyerahkan hampir seluruh hartanya demi berkurban. Padahal, secara agama, ia tidak wajib. Ia malah berhak menerima daging kurban.
“Kenapa ingin berkurban, Nak?” tanya Haji Sanusi perlahan.
“Saya ingin jadi pemberi, bukan terus-menerus jadi penerima. Saya ingin bisa memberi daging kurban ke orang lain.”
Haji Sanusi mengangguk, matanya berkaca-kaca. “Baik. Senin nanti, uangmu akan saya ambilkan.”
Senyum Inak Ma’nah merekah. Langkahnya ringan saat pulang. Di belakang, Haji Sanusi termangu. Ia bertanya dalam hati: kapan Inak Ma’nah belajar makna kurban? Dari mana ia memahami bahwa memberi, meski dalam kekurangan, adalah puncak keikhlasan?
Sementara banyak orang yang sudah berhaji tak berubah sikap, Inak Ma’nah—yang mungkin tak akan pernah punya cukup uang untuk ke Tanah Suci—telah mencapai derajat itu. Ia belum berhaji, tapi jiwanya sudah mabrur.
Hari itu, Haji Sanusi merasa malu. Ia, yang dilarang dokter makan daging kambing, bertekad akan melanggar pantangan itu. Demi menikmati daging kurban milik perempuan yang hatinya terasa lebih bersih dari siapa pun yang ia kenal.
Daging itu mungkin sederhana, tapi aromanya... seolah berasal dari surga.












































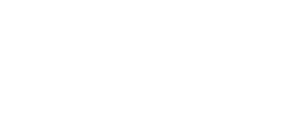
Jamiri Adnan
21 November 2024 15:01:25
Kami sebagai masyarakat sangat mendukung adanya kegiatan pelatihan jurnalistik yang di selenggarakan...